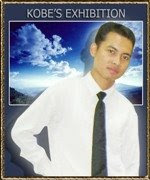Imperialisme adalah tahapan tertinggi dan yang terakhir dari sejarah perkembangan kapitalisme. Karena setelah Abad ke-20, monopoli mendominasi segi-segi ekonomi dan politik di dalam masyarakat secara utuh di negara-negara kapitalis besar. Alat-alat produksi maupun kapital uang dikontrol oleh segelintir kapitalis monopoli. Penguasaan dari kedua hal tersebut sangatlah penting dan dibutuhkan oleh industri. Dominasi ini adalah lonceng kematian bagi sistem kapitalis yang menguasai seluruh dunia.
Adalah sebuah keharusan bagi kita untuk mempelajari karakter dari imperialisme agar kita mengetahui bagaimana caranya kita menghancurkannya dalam Revolusi Proletariat Dunia dan Revolusi Nasional kita.
A. LIMA KARAKTER IMPERIALISMEA.1 Konsentrasi Produksi dan MonopoliKonsentrasi produksi dan monopoli terjadi melalui perkembangan dan pembangunan industri yang berlangsung cepat, sehingga terjadi penumpukan kapital di tangan segelintir kapitalis. Ini adalah proses bagaimana dominasi dan monopoli produksi terjadi dalam masyarakat. Konsentrasi produksi adalah hasil dari persaingan bebas dan penumpukan modal (utamanya modal mesin produksi, bahan mentah, dan peralatan produksi lainnya). Dalam waktu krisis, proses ini akan semakin cepat berlangsung. Karena banyak kapitalis kecil yang tersingkir atau hancur, dan segelintir kapitalis besar akan semakin menggurita. Monopoli akan menggantikan persaingan bebas dan mendominasi produksi dengan total (artinya juga mendominasi masyarakat). Perkembangan produksi yang cepat mendorong konsentrasi kapital. Industri besar dengan mesin dan teknologi maju dan memproduksi dalam skala yang besar adalah industri yng paling tepat untuk keberadaan monopoli. Konsentrasi produksi dan monopoli akan terjadi melalui berbagai jalan:
a. perjanjian tentang harga dan penjualan yang tidak konsisten, dan berbasis pada konsensus dan pemenuhan sukarela dari mereka yang membuat produk.
b. firma kartel dan asosiasi para monopolis.
c. konzern atau perusahaan induk (holding company).
d. merger, dengan berbagai jalan, yaitu: menjadi anggota dalam cabang industri yang sama, hanya terlibat dalam berbagai pemrosesan bahan mentah, produsen untuk bahan mentah dan perantara bagi produk tertentu, terlibat dalam berbagai lini produksi namun berada di bawah satu korporasi.
Selama waktu persaingan bebas, tipe dari sebuah perusahaan adalah “murni”, maksudnya adalah perusahaan tersebut hanya memproduksi satu jenis produk. Akan tetapi selama masa imperialisme, mereka tidak lagi memproduksi satu jenis produk. Karena para kapitalis monopoli ingin memjaga rata-rata keuntungan yang stabil melalui menurun atau (bila tidak) memindahkan pertukaran dalam perdagangan. Walaupun dia mendikte pasar tapi juga harus melakukan aktivitas tersebut untuk memastikan dan menjamin mereka dapat memenangkan persaingan di antara perusahaan yang melakukan merger. Di sini pembangunan teknologi mungkin untuk diakumulasi. Sehingga pendapatan yang lebih besar juga diperoleh di samping pendapatan umum yang biasa yang diperoleh. Ini yang memperkuat posisi mereka dalam krisis.
Monopoli dapat dengan sangat menentukan mendominasi seluruh perekonomian, karena sebagian besar kapital industri dan produksi terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan besar atau kelompok kecil dari para kapitalis. Ada tiga tahap bagaimana monopoli tumbuh dari persaingan bebas, yaitu:
• 1860-1870, puncak dari persaingan bebas di negara kapitalis pada saat revolusi industri yang dimulai dari Inggris.
• 1873-1890, periode transisi di mana banyak perusahaan dan kapitalis kecil yang mulai runtuh dan merger atau diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar.
• 1900-1903, krisis yang semakin membuat kapitalis kecil runtuh dan dimulainya monopoli.
Kapitalisme monopoli menjadi fondasi dari sistem kapitalisme di negeri kapitalis. Contoh: Di dekade 80-an, 500 perusahaan terbesar Amerika Serikat menguasai 15% dari seluruh industri, memperkerjakan 68% buruh, mengendalikan 60% dari total penjualan, dan mendapatkan 71% dari keuntungan di seluruh dunia.
Monopoli di samping menggabungkan berbagai kapitalis dan perusahaannya, dia juga menghancurkan mereka. Contoh: Di tahun 1955, terdapat 500 perusahaan terbesar di dunia. Tahun 1986, 186 dari perusahaan-perusahaan tersebut telah dibeli. Sedangkan 262 dari perusahaan tersebut membeli 4500 perusahaan yang lain. Artinya dari 500 perusahaan terbesar di dunia pada tahun 1955, pada perkembangannya menjadi 186 perusahaan dicaplok atau hancur dan di lain pihak 262 perusahaan besar yang lainnya tumbuh semakin kuat dan menguasai perekonomian dunia. Pada dekade 1980-an dan 1990-an adalah era megamerger. Total nilai merger dan pembelian perusahaan oleh perusahaan besar Amerika Serikat adalah sebagai berikut: 1975 senilai 12 Milyar Dollar Amerika Serikat, 1981 senilai 83 Milyar Dollar Amerika Serikat, 1985 senilai 200 Milyar Dollar Amerika Serikat.
Akibat dari dominasi monopoli industri adalah mereka mengendalikan sumber sumber bahan mentah, produksi, harga dan pasar, teknologi, ketrampilan produksi, dan pembagian laba. Bahkan perkembangan terkininya adalah mengendalikan persediaan dan
membuat monopoli dalam harga. Proses penghisapan laba super yang lebih besar mereka dapat dari buruh dan kapitalis kecil, bila dalam proses mengeruk laba super mendapat ganjalan akan menggunakan jalan kekerasan dan memperkuat dominasinya di dalam sprastruktur (ini yang membuat banyak perang). Kontradiksi yang demikian yang akan membuat krisis semakin menghebat di era imperialisme.
A.2 Kapital Finans (Uang) dan Oligarki Keuangana. Kapital UangSelama masa persaingan bebas, bank hanya mediator dalam penjualan dan pertukaran produk. Bank mengumpulkan pendapatan (uang) dari para kapitalis dan Rakyat pada umumnya, peranannya pasif. Namun dalam era imperialisme, uang yang masuk didistribusikan oleh bank melalui pinjaman sehingga dia mulai masuk dalam kegiatan produksi. Peranan bank menjadi sangat dibutuhkan oleh kapitalis, karena bank juga dapat digunakan untuk menambah kapital. Di sini peran bank yang dibentuk oleh kapitalis menjadi aktif (bahkan kapitalis jugamembangun bank-nya sendiri untuk semakin banyak mengeruk keuntungan).
Selama masa persaingan bebas, bank dapat laba dari bunga pinjaman kapitalis. Proses ini yang membuat uang menjadi aktif. Dalam masa imperialisme, bank tidak hanya dapat laba dari bunga pinjaman, namun laba tersebut digunakannya lebih lanjut untuk investasi (menanamkan modal pada kegiatan produksi). Dalam beberapa kasus
pemilik bank juga seorang kapitalis produksi (atau sebaliknya), ini yang memudahkan mereka bekerja sama dalam melakukan penanaman kapital.
Produksi dan keuangan punya hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, karenanya banyak kapitalis industri yang membangun korporasi keuangan (bank) sendiri.
Dalam masa krisis dewasa ini di negara terjajah atau setengah jajahan, bantuan negara imperialis atau lembaga-lembaga imperialis akan ditujukan pada sektor keuangan, karena imperialisme butuh alat untuk mendistribusikan kapital dengan cepat (bank adalah pilihan utamanya). Tak heran di Indonesia, program bantuan IMF utamanya ditujukan pada rekapitalisasi perbankan.
Contoh: Di tahun 1980 terdapat 12 bank terbesar di Amerika Serikat yang mengontrol 22% dari kepemilikan lokal dari 14.500 bank (75%-nya berada di luar negeri). Kelompok Rockefeller mengontrol 16 bank dan berbagai perusahaan keuangan dengan kekayaan 121,8 Milyar Dollar Amerika Serikat. Di antara bank juga saling bunuh atau merger. Di Jepang, 20 bank memeiliki kekayaan 995,8 Milyar Dollar AS. Enam dari bank-bank tersebut memiliki kekayaan 554 Milyar Dollar AS. Di Amerika Serikat, 17 kelompok industri dan keuangan terbesar mengendalikan 420 korporasi besar. Di antara mereka terdapat 197 kelompok yang memiliki kekayaan 1 Milyar Dollar. Di Jepang, Kelompok “Modern Zaibatsu” memiliki 190 kelompok anggota (di antaranya Mitsubishi, Fuji, Sanwa, Sumitomo, Daichi, Kangyo, dan lain-lain). Mereka juga menguasai 8746 perusahaan lainnya.
Karena kapital uang dan oligarkhi keuangan, anggaran pengeluaran dari pemerintah Amerika Serikat sangat besar. Terutama untuk menjaga bonds. Di tahun 1981, pemerintah Amerika Serikat setiap harinya menjual 20 Milyar Dollar AS worth of bonds, 10 tahun kemudian naik menjadi 124 Milyar Dollar AS. Bonds memiliki bunga
tinggi dan menjadi pendapatan yang tinggi untuk oligarkhi keuangan. Di IMF, Amerika Serikat mempunyai banyak hutang, tapi dia dapat menunggak pembayarannya karena menguasai lembaga tersebut.
b. Akibat dari Dominasi Kapital Uang dan Oligarkhi KeuanganAkibat yang terjadi adalah:
• Dominasi yang cepat dari bank-bank besar.
• Intensifikasi karakter parasit dari Kapitalis Monopoli.
• Penumpukan laba super yang semakin besar.
Bank menjadi pusat distribusi kapital uang ke berbagai negara (bahkan juga digunakan sebagai alat produksi). Denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat tergantung dari bank-bank besar dari praktek peribaannya. Parasitisme dari kapitalis monopoli dilakukan melalui spekulasi, perjanjian penanaman modal tanpa melibatkan diri dalam proses produksi. Mereka menerima untung yang berlebihan dari “pajak” yang dibayarkan oleh para kapitalis produksi untuk pembelian suatu produk atau dari bunga pinjaman. Laba super mereka dapat dari shares, bonds, commission dalam produksi dan penjualan.
c. Perubahan yang Terjadi di Negara Imperialis selama Kapitalisme MonopoliImperialisme tidak hanya busuk di lapngan ekonomi, tetapi juga di lapangan politik. Konsentrasi imperialisme pada kedua lapangan tersebut akan berjalan berbarengan, karena mereka juga “memerintah” negara lain. Kapitalis monopoli mempunyai kekuasaan terhadap pemerintah negera imperialis, mereka merubah karaktek pemerintah dari “perwakilan dari seluruh kapitalis” menjadi “wakil dari satu kekuatan kapitalis monopoli”. Mereka memegang kendali yang penuh atas segala segi suprastruktur di dalam masyarakat (politik, budaya dan alat-alat pelaksananya: pemerintahan dan media massa). Bantuan keuangan dari kapitalis monopoli adalah bantuan terpenting dan menentukan dalam kegiatan politik borjuis, misalnya: dana kampanye pemilihan. Bekas bekas aparat militer dan birokrasi neegara borjuis yang melayani kapitalis monopoli ketika pensiun akan menjadi pejabat di lingkungan bisnis mereka. Bahkan sebelum menjabat mereka juga orang penting di dalam bisnis kapitalis monopoli (ingat all the president’s men di sekitar George W. Bush Jr. Presiden Amerika Serikat saat ini adalah pemegang posisi penting di industri minyak dan senjata). Sehingga status istimewa akan didapat dalam bisnis.
Kapitalis monopoli mempunyai asosiasi dalam berbgai industri yang memonitor kebijakan pemerintah sehingga dapat menguntungkan mereka. Kebijakan yang penting akan dibuat dan dilaksanakan oleh perwakilan mereka di pemerintahan (baik eksekutif ataupun legislatif). Kondisi ini yang akan merubah kapitalis monopoli menjadi kapitalis
monopoli negara. Perang Dunia I mengintensifkan transformasi kapitalis monopoli menjadi kapitalis monopoli negara. Contoh: Dominasi fascis di negara Italia, Jerman, dan Jepang. Di lain pihak, Amerika serikat dan Inggris mempunyai “new deal” atau perjanjian baru bagi kegiatan ekonomi di antara mereka karena tajamnya persaingan dan
kontradiksi di antara mereka dalam industri militer. Sampai sekarang kontrak terhadap bisnis militer menjadi sumber laba super bagi kapitalis monopoli. Anggaran militer Amerika serikat setelah runtuhnya rezim revisionis modern di Uni Soviet adalah sebesar 250 Milyar Dollar AS (bandingkan dengan anggaran mereka pada saat perang dunia I yang sebesar 10 Milyar Dollar AS). Kompleks industri militer mereka akan selalu menginginkan perang, agar mereka selalu mendapat permintaan pembelian senjata.
Selama era imperialisme, negara memiliki peran penting dalam menarik laba super bagi kapitalis monopoli melalui kebijakan yang memudahkan mereka dalam bisnis di sistem kapitalis. Contoh: Bank Dunia mendikte kebijakan sebuah negara yang akan “dibantunya” sebagai “konsekuensi” dari “bantuan”. Cara yang dilakukan sekarang adalah melalui program “globalisasi”, mereka memindahkan krisis di negara imperialis kepada negara-negara terjajah atau setengah terjajah untuk menyelamatkan kapitalis monopoli. Penindasan terhadap rakyat di negeri jajahan atau setengah jajahan membuat banyak aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh kelas proletar maupun Rakyat.
Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian di negara imperialis mengalami pertumbuhan yang cepat. Karena negara saingan mereka (kekuatan imperialis fascis pimpinan Jerman) mengalami kekalahan perang yang hebat dan menghancurkan sarana produksi mereka. Bahkan Amerika Serikat mempelopori kegiatan ekport surplus kapital ke negara-negara tersebut melalui Marshall Plan. Ini yang mendorong perkembangan besar dalam produksi kapitalis dari negara-negara imperialis pimpinan Amerika Serikat. Namun sebelum tahun 1970 pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat berhenti, karena anarkisme produksi yang mereka lakukan dan menajamnya kontradiksi antara klas proletar dan borjuis di seluruh dunia. Jutaan buruh dipecat oleh para kapitalis untuk mengurangi biaya produksi dan tentu saja meningkatkan profit. Dari tahun 1990 sampai 1994.
Dalam situasi tersebut, pajak yang dibayar rakyat juga bertambah karena negara harus menjaga keseimbangan ekonomi agar sumber kekuatan ekonomi mereka dari kapitalis monopoli dan imperialisme tidak hancur. Sangatlah bertentangan ketika Rakyat harus membayar pajak yang tinggi namun di saat bersamaan juga harus dibebani dengan naiknya biaya pelayanan publik dan sosial karena negara harus mengurangi subsidinya untuk sektor itu dan dialihkan pada bantuan penyehatan industri kapitalis monopoli. Penggunaan media massa, periklanan, dan budaya borjuis sebagai senjata ideologi kapitalis monopoli dimaksimalkan untuk menjinakkan buruh dan Rakyat. Isu yang lain seperti rasisme atau praktek neo-fascisme dari pendukung mereka meningkat untuk mengalihkan isu perjuangan kelas melawan imperialisme.
A.3 Ekspor KapitalSelama era imperialisme ada polarisasi negara di dunia, yaitu: negara-negara kapitalis kaya yang diuntungkan dari penanaman modal dan meminjamkan hutang ke negara yang lain, dan negara-negara yang kekurangan modal, terjerat hutang, dan selalu mendapat penanaman modal langsung dari negara kapitalis kaya (jumlah negara-negara ini lebih besar).
Eksport kapital berkembang dari hasil akumulasi kapital. Agar tidak terjadi krisis over-produksi karena surplus kapital, maka mereka mengeksportnya ke luar negeri. Alasan utamanya adalah untuk memproteksi dan menambah pendapatan mereka dan rata-rata keuntungan. Sasaran dari eksport kapital adalah negara-negara yang terjajah dan setengah jajahan, ini adalah praktek baru dari kolonialisme atau disebut juga dengan neo-kolonialisme.
Sejak negara terjajah dan setengah terjajah sangat terbelakang dalam industri, mempunyai sedikit kapital, upah buruh yang murah, memiliki cadangan bahan mentah yang luas dan harga tanah yang murah, maka keuntungan dari penanaman modal dari eksport kapital akan didapat. Bentuk-bentuk dari eksport kapital adalah direct invesment atau penanaman kapital langsung (bentuk ini utamanya ditujukan di negara setengah jajahan), pinjaman hutang, bantuan strukturisasi industri manufaktur, bantuan (semacam hibah), dan lain-lain.
Bagaimana negara-negara imperialis menggunakan eksport kapital untuk menarik laba super? Statistik dari PBB menunjukkan bahwa pada dekade 70-an dan 80-an Amerika Serikat mengalokasikan 72,6 Milyar Dollar untuk penanaman langsung di negara terjajah dan setengah jajahan (60% di antaranya di kawasan Asia Tenggara). Keuntungan yang didapat adalah 139,7 Milyar, atau dalam setiap 1 Dollar mereka mendapat keuntungan 1,2 Dollar. Untuk dekade selanjutnya total penanaman modal mreka bertambah menjadi 213,4 Milyar Dollar (157 Milyar untuk negara-negara berkembang dan 52,6 Milyar untuk negara-negara yang sama sekali terbelakang). Investasi Jepang ke luar negeri di tahun 1989 adalah sebesar 67,5 Miyar Dollar (terbesar dari semua negara imperialis di tahun itu). Total nilai dari investasi ke luar negeri mereka adalah 352,4 Milyar Dollar (nomor 2 setelah Amerika Serikat).
Keuntungan yang didapat oleh negara kaya dari investasi tidak dapat diketahui secara pasti karena mereka menggunakan transferpricing atau imbal beli (terutama untuk industri minyak). Cara kerja sistem ini adalah bahan mentah dan produk dibeli oleh tambahan negara terbelakang dari perusahaan induk mempunyai harga yang lebih tinggi.
Bagaimana Imperialis mendapat keuntungan dari pinjaman dan bantuan? Mereka menggunakan pinjaman dan bantuan untuk mendikte kebijakan ekonomi dan politik dari negara terjajah atau setengah jajahan yang mereka beri kredit. Dari kontrak besar tersebut mereka akan membuka pasar untuk kepentingan produk mereka (liberalisasi).
Agar pemerintah bisa bayar hutang, mereka harus menurut sama imperialisme. Sejak krisis hutang dunia dimulai ada berbagai tahap yang dilakukan IMF untuk keluar dari krisis dan membayar hutang. Mereka membiarkan industri dan pelayanan sosial rusak dan dapat pendapatan dari export dan pekerja-pekerja migran. Mereka juga dapat pemasukan dari perusahaan kebijakan perusahaan pemerintah untuk membayar hutang.
Pada tahun 1984, jumlah yang mereka dapat dari negara-negara miskin (mayoritas dari bank komersial) sebanyak $ 20-30 juta. Kemudian total pembayaran dari dunia ketiga hampir 3 kali lipat dari total hutang yang mereka dapat untuk keluar dari krisis. Dalam dunia ketiga jumlah pengangguran sebanyak 1 milyar orang. Mereka hanya mendapat 98 cent perhari. Tahun 1990 jumlah pengangguran meningkat menjadi 1,3 milyar.
Hutang bisa berupa pinjaman kepada pemerinyah atau swasta, karena ada perjanjian bilateral, multilateral dengan negara atau intitusi. Hutang swasta punya bunga yang tinggi dan jangka waktu yang singkat.
• 60% dari total pinjaman dari Jepang kepada negara-negara di Asia, kemudian sebagian besar pinjaman Jerman juga ke Timur, sedangkan pinjaman AS yang terbesar ke pemerintahan bonekanya (Israel, Mesir, Polandia (untuk urusan minyak)). Bagian terbesar dari pinjaman ini adalah bantuan sarana dan prasarana militer.
Mereka mengatakan bahwa tahun 1960 adalah dekade dari pembangunan, yang menghasilkan jurang yang luas antara negara kaya dan miskin. Dekade ini yang pemperburuk kesejahterahan, situasi dan kondisi. Hutang pemerintah di dalam 12 negara-negara Masyarakat Eropa (European Community) adalah $ 4.000 Milyar (1994), kemudian meningkat $ 4.900 Milyar (1995). Di negara kaya mereka memakai praktek monopoli untuk menghindari hutang itu. Banyak bank Jepang meminjamkan uangnya ke pemerintahan Amerika.
Bagaimana negara terbelakang dieksploitasi melalui perdagangan kolonial? Eksport kapital menghasilkan penjualan yang sangat besar, aboundant dan bahan mentah yang murah dan makanan untuk menurunkan biaya produksi dan sehingga meningkatkan jumlah laba. Di samping investasi langsung , mereka juga mengeksport mesin dan alat produksi maju, maka negara Dunia Ketiga sangat tergantung. Ini adalah alasan mereka untuk membuka pasar bagi eksport industri dari negara imperialis. Monopoli imperialis untuk produk indusrti (mesin dan BBM siap pakai). Mereka membeli bahan mentah dari negara Dunia Ketiga. Negara miskin harus mengeksport jumlah besar komoditasnya untuk mengejar kualitas nilai eksportnya.
Menurut PBB harga eksport dalam negara importir, adalah : 1980-100, 1992-48 (harga barang import lebih mahal dari barang ekspotnya) ini ratio harga di tahun 1992 kalau mau seimbang harus melipatgandakan jumlah eksport. Ratio yang tidak seimbang dari ekonomi perdagangan di negara miskin. Maka mereka selalu defisit (dan meningkat setiap tahun). Mereka harus menjual terus sumber daya alamnya.
Dari kenyataan ini kemunduran negara miskin adalah keuntungan bagi imperialime untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Jadi sulit bagi negara miskin untuk maju menjadi negara industri. Bagi Korea Selatan dan Taiwan menjadi negara industrial dengan alasan politik dari AS untuk melawan Korea Utara dan China (hanya menjadi dekorasi bagi imperialisme). Mereka adalah kapitalis yang tergantung, maka sekarang ketika tidak dibutuhkan jatuh juga. AS harus membantu mereka untuk mengeksport komoditas yang murah (kain, baju, dan lainnya). Mereka tergantung dalam teknologi dan pasar (Jepang/AS). Mereka (Korsel/Taiwan) tidak bisa menahan, karena pasar yang sempit. Teori kapitalis dependen gagal.
A.4 Pembagian Dunia di antara Negara-negara KapitalisBagaimana konsentrasi kapital dan produksi terjadi di dunia? Dominasi monopoli yang secara terus menerus akan mengakibatkan konsentrasi kapital dan produksi. Kekayaan negara dihabiskan oleh beberapa negara imperialis. Monopoli internasional adalah satu dari karakterisktik imperialisme.
Sebelum PD II alatnya adalah organisasi atau perjanjian internasional. Setelah PD II, Multi-National Corporation (peruasahaan dari berbagai negara) dan Trans National Corporation (perusahaan lintas negara) adalah bentuk monopoli internasional. MNC adalah perusahaan yang dikendalikan dan berbasis di satu negara (AS, Jepang, Jerman, Uni Eropa). TNC adalah perusahaan dengan sistem manajemen membagi kepemilikan, penjualan, manager, dan pekerja, perusahaan dipecah di berbagai negara. TNC muncul di Eropa, selama masa kapitalis monopoli ketika dua negara atau lebih muncul untuk melakukan persaingan dengan MNC dari AS, contohnya: 5 MNC terbesar atas produk konsumsi menguasai 70% pasar dunia. Lima MNC terbesar atas produk otomotif, pesawat, penerbangan, barang-barang elektronik dan baja menguasai 50% produksi. Lima MNC terbesar dalam industri minyak, komputer dan media massa memproduksi sebanyak 40% dari penjualan dunia.
MNC mulai mendominasi setelah PD II karena setelah perang, industri menurun dan AS hanya satu-satunya negara yang masih kuat sehingga terjadi akumulasi kapital yang cepat untuk kemudian memacu perkembangan teknologi di AS. Kapitalis monopoli mendapat keuntungan untuk memperoleh bahan mentah dan buruh murah di berbagai negara. Negara kapitalis monopoli bertanggungjawab terhadap bantuan pada MNC untuk melakukan ekspansi industrinya melalui bantuan resmi (pinjaman pemerintah). Misal: pemerintah AS jika memberi bantuan (bilateral/ multilateral) pada suatu negara akan selalu diikuti oleh MNC-nya.
Akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi kapital dan produksi dalam perkembangan dan hubungan antar negara:
1. Pembangunan yang tidak merata (uneven development) antar negara industri dan negara miskin.Pada negara-negara miskin akibatnya: terjadi ekspolitasi secara terus menerus baik terhadap Rakyat maupun sumber daya alamnya, penurunan kesejahterahan karena bila terjadi krisis di negara imperialis dan para kapitalis monopoli memindahkannya ke negara terjajah atau setengah jajahan maka sektor pelayanan publik akan dipangkas pembiayaannya oleh pemerintah negara boneka, industrialisasi di negara tersebut terhambat.
Jurang ini yang akan membuat penindasan terjadi semakin menghebat di negara miskin. Kepentingan imperialisme akan bersinggungan dengan kepentingan kelas reaksioner di negara miskin (tuan tanah, borjuis komprador, dan kapitalis birokrat). Dalam kehidupan ekonomi negara tersebut, banyak kapital yang masuk dalam ke dalam hubungan produksi lama sewa tanah, laba perdagangan hasil pertanian lebih banyak menguntungkan borjuis komprador dan kapitalis birokrat yang menguasai distribusinya, dan praktek perdagangan tengkulakisme atau peribaan semakin merajalela. Sehingga imperialisme tetap melanggengkan sistem ekonomi lama (yaitu feodalisme atau setengah
feodalisme).
Pembangunan yang sangat lambat dari negara miskin sangat berguna bagi imperialis. Mereka dipaksa untuk bergantung pada investasi asing, mesin, dan teknologi tinggi, dan juga harus memberikan bahan mentah dan buruh yang murah. Imperialis akan mendikte negara miskin untuk menjadi eksportir bahan mentah yang murah dan menjadi
importir produk maju dari negara imperialis yang mahal. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dari pembangunan lokal di negara miskin. Oleh karena itu negara miskin tidak akan bisa mempunyai surplus dalam pendapatan negara. Di berbagai negara persoalan ini meluas pada kelaparan karena sumber daya nasional disedot habis-habisan untuk membayar hutang, menutup defisit, dan lain-lain. 40 ribu anak di negara miskin mati karena kelaparan, kurang gizi, dan malnutrisi. Bahkan di negara miskin juga harus mengeksport buruh migran yang murah. Kriminalitas dan prostitusi meningkat karena rendahnya produktivitas.
2. Pembangunan yang tidak merata di antara negara-negara imperialis.Sentralisasi kapital dan produksi internasional memperhebat persaingan antar negara imperialis. Selama PD II, produksi industri AS meningkat, ketika negara imperialis yang lain colapse. Ini yang membuat dollar menjadi mata uang yang dominan dalam sistem keuangan internasional. Ketika kondisi perekonomian megara-negara Eropa Barat dan Jepang (pada dekade 70-an) bangkit, maka kompetisi dengan AS juga naik. Sekarang konfigurasinya tetap AS, Jepang dan Uni Eropa (mereka membuat benteng bersama, namun bukan berarti tidak ada kontradiksi di antara mereka. Peristiwa Agresi Militer Amerika Serikat di Iraq awal tahun 2003, nyaris mempertajam kontradiksi di antara mereka).
Walaupun AS menang dalam Perang Dingin, dia lemah dalam ekonomi, dia terjerat hutang dan defisit anggaran (karena konsentrasi di militer). Walaupun AS coba untuk memperkuat industrinya, dia tidak bisa melakukannya karena defisit anggaran, hutang dan rusaknya hubungan dengan aliansinya sejak dekade 70-an(terutama dengan
negara-negara Eropa Barat non-Inggris).
Dari Eropa pun ada pembangunan yang tidak merata di negara imperialis. Unifikasi Jerman di tahun 1990 setelah runtuhnya Tembok Berlin, membuat mereka mempunyai kekuatan produksi dan pasar yang lebih besar dibandingkan negara lain. Situasi sekarang di Inggris sangat berbeda dengan dominasi sebelumnya pada pasar dunia di awal berkembangnya sistem kapitalisme di Eropa.
3. Persengkongkolan dan kontradiksi dalam scope internationalWalaupun kapitalis monopoli internasional bersengkongkol melawan kelas proletar di seluruh dunia dan tetap tidak ada genjatan senjata. Konsentrasi kapital dan produksi di dunia tetap akan mengurangi jumlah kapitalis karena saling bunuh. Namun konsentrasi ini akan menambah kapital bagi kapitalis yang menang. Dan melalui kontradiksi ini, pembagian ekonomi dunia terjadi di kekuatan imperialis. “Kapitalis membagi dunia tanpa malice, tetapi sebelum mereka mencapai tingkat konsentrasi yang mendorong mereka untuk berlindung dalam kaitannya untuk memperoleh laba. Dan mereka membagi negara berdasarkan jumlah kapital, berdasarkan kekuatan. Sebelumnya tidak ada jalan untuk mendistribusikan hasil komoditas produk dan kapital. Tetapi kekuatan berubah menurut tingkat perkembangan ekonomi” (Lenin).
Karena tidak ada perlawanan dari negara sosialis, kekuatan imperialisme dengan mudah membagi dunia. Saat Perang Dingin imperialisme melawan habis-habisan. Walaupun mereka bersengkongkol, mereka juga berkompetisi dalam membagi-bagi kembali negara. Pembagian ini karena krisis over produksi dan mereka butuh pasar yang lebih luas. Ini yang membuat kompetisi tidak pernah berhenti. PBB, IMF, WB, G7, WTO, Uni Eropa merupakan persekongkolan multilateral dan menambah keuntungan mereka yang membawa kehancuran negara Dunia Ketiga. Di dalam agensi-agensi ini, kapitalis monopoli dari berbagai dunia bergabung. Tapi partisipasinya sesuai dengan kekuatan komparatif. Karena AS sangat kuat, maka secara relatif dia yang dominan. Dari sini pembagian dunia secara ekonomi diantara negara imperialis terjadi.
A.5 Pembagian Dunia di antara Kekuatan BesarBagaimana pembagian tersebut dilakukan? Secara bersama-sama dengan konsentrasi menurut pembagian ekonomi dunia, hubungan di antara negara-negara dimunculkan menurut pembagian teritorial dunia dalam perjuangan untuk mempengaruhi, perjuangan untuk kolonialisasi dan neo-kolonialisasi. Selama masa imperialisme, pembangunan teknologi melaju yang membutuhkan wilayah yang lebih besar untuk meletakkan surplus kapital dan mendapatkan bahan mentah. Karena alasan itu, mereka mengintensifkan kebijakan kolonialisasi untuk mengontrolnya dan menjaga dari pesaingnya. Selama masa kompetisi bebas, kolonialisme diterapkan karena terdapat kondisi di mana masih banyak wilayah yang “kosong” di dunia. Selama era imperialisme, kekuatan imperialis sudah membagi dunia dengan total. Saat itu negara-negara di bagi menjadi 2, yaitu: pengeksploitasi dan yang di eksploitasi.
Setelah PD II, negara-negara sosialis tumbuh dan meluasnya gerakan pembebasan nasional di dunia. Maka kekuatan imperialis dunia menghapus penjajahan (kolonialisme lama) dan merubah menjadi neokolonial. Bagaimana mereka mengkontrol negara-negara miskin dalam cara neo-kolonialisme? Yaitu melalui operasi kapital uang (bank). Karena dia yang punya kekuatan terbesar di atas kekuatan ekonomi dan hubungan internasional. Walaupun era kolonialisme sudah lewat, tetap ada banyak jalan bagi imperialis untuk mengontrol. Diantaranya:
1. Melalui cara kriminalisasi. Pemerinyah yang melawan negara imperialis akan diblokade secara perdagangan, hutang, investasi, tindakan militer, subversi, spionase, propaganda, dll.
2. Mereka memperlakukan secara tidak adil dalam perjanjian multilateral/bilateral.
3. Meraka masuk dalam politik dalam negeri, mereka mendukung para pemimpin dari kelas reaksioner dalam negeri maupun partai politik yang menjadi representasi kelas tersebut.
4. Mereka mengontrol permintaan senjata dan tekhnologi militer dan melatih para perwira militer dari angkatan bersenjata pemerintahan boneka mereka atau kelas reaksioner.
5. Mereka memakai agensi regional dan internasional. Seperti misalnya: ASEAN, SEATO, dll.
6. Mereka menyerang rakyat dengan serangan kultural dan praktek ideologisasi borjuasi.
Imperialisme berarti perang dan persiapan untuk perang
Pembagian dunia secara ekonomi dan teritorial telah lengkap, tetapi kekuatan ekonomi dan politik negara imperialis berubah melalui pembangunan yang tidak merata mereka. Pembagian dunia yang ada hanya temporer.
Selama era imperialisme, satu kekuatan imperialis hanya dapat menguasai dengan menghancurkan kekuatan imperialis yang lain. Hasilnya adalah perang. Ketika kapitalisme masuk ke tingkatan imperialisme, telah terjadi dua Perang Dunia. Imperialisme juga memanipulasi perbedaan di antara negara kecil dan lemah untuk saling
perang demi keuntungannya.
Kebanyakan kekuatan senjata imperialis diarahkan kepada gerakan pembebasan dan proletar. Hanya revolusi proletar yang dapat memberhentikan perang imperialis. Perang imperialis akan terus terjadi selama tidak ada gerakan Revolusi Proletariat Dunia.
Walau tidak ada perang, negara imperialis selalu siap untuk perang. Mereka menjaga tentara mereka untuk selalu siap berperang. Di lain pihak produksi senjata adalah bisnis yang menguntungkan bagi kapitalis monopoli. Bagi kapitalis monopoli, perang adalah sumber laba terbesar. Ini membuktikan bahwa imperialisme akan membusuk dan mengintensifkan kontradiksi pokok.
B. REVOLUSI PROLETARIAT DI ERA IMPERIALISMEB.1 Kenapa Imperialisme Merupakan Awal dari Revolusi Sosialis?Kapitalisme telah berada di tingkatan terakhir, tingkatan dari transisi untuk menuju ke sistem masyarakat yang lebih tingg, yaitu sosialis. Kalau sudah mencapai tahap imperialisme, dia akan semakin matang untuk revolusi sosialis. Dia menciptakan kondisi obyektif untuk memajukan sejarah dunia ke level baru dan lebih tinggi. Over produksi, monopoli, oligarkhi, penindasan dan penghisapan di negara-negara miskin adalah praktek yang mereka lakukan selama ini. Ketika terdapat sosialisasi produksi dan tenaga kerja pada tingkatan yang tinggi, akan terdapat pula kekacauan sosial karena adanya akumulasi produksi dan kapital secara perorangan. Krisis umum imperialisme melewati 3 tahap :
1. Perang Dunia I (1914-1918), disini ada Revolusi Sosialis Besar Oktober 1917 di Rusia yang dipimpin oleh Kelas Proletar melalui Partai Bholsevik.
2. Depresi besar di tahun 1930 yang menghasilkan Perang Dunia II (1939-1945), yang memacu tumbuhnya negara sosialis di Eropa Timur, China, Korea Utara, Vietnam.
3. Setelah Perang Dunia II, kontradiksi internal yang destruktif pada sistem kapitalisme. Kemudian Perang Dingin melawan negara-negara sosialis dan seluruh Gerakan Pembebasan Nasional di berbagai negeri. Namun pada tahun 1956 terjadi pengkhianatan kaum revisionis-modern pimpinan Nikita Khruschev di Uni Soviet. Gerakan Komunis Internasional mencatat bahwa pada tahun 1966 sampai dengan pertengahan 1970 terjadi Revolusi Besar Kebudayaan Proletar di Republik Rakyat China, dan disusul kemenangan Pembebasan Rakyat Indochina dan Vietnam terhadap dominasi imeprialis Amerika Serikat.
Leninisme adalah Marxisme di era imperialis dan Revolusi Proletar Dunia. Marxisme-Leninisme sanggup:
• Mengklarifikasi dan memperbaiki pembangunan teori dan praktek Revolusi Proletar selama masa imperialisme (hasil gemilang yang dicapai Rakyat Rusia di tahun 1917, Rakyat Tiongkok 1949, dan Pembebasan Nasional Vietnam 1945, 1955, dan 1975 adalah bukti nyata kemajuan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi GerakanProletar Dunia).
• Mengklarifikasi kemenangan dan pencapaian dari revolusi sosialis adalah mungkin di satu negari, karena kapitalisme sudah mematang untuk revolusi pada era imperialisme.
• Revolusi akan mencapai kemenangannya pada rantai imperialisme yang terlemah.
• Menekankan pada pentingnya gerakan pembebasan nasional di negeri terjajah dan setengah-jajahan.
• Kebutuhan akan kepemimpinan kelas proletar melalui detasemen termajunya dalam sebuah Partai Kelas Proletar Tipe Baru dalam perjuangan revolusioner rakyat di suatu negara.
• Mengklarifikasikan dan memgembangkan teori dan praktek Diktatur Proletariat yang akan memimpin masyarakat menuju komunisme.
B.2 Mengapa di era imperialisme, perjuangan anti-imperialisme di negari terjajah atau setengah jajahan merupakan bagian dari Revolusi Proletar Dunia?Kebijakan negara imperialis memyebabkan kemiskinan pada rakyat di negeri jajahan dan setengah jajahan. Ini yang menyebabkan tujuan perjuangan anti-imperilame mereka merupakan bagian yang tidak terelakkan dari Revolusi Proletar Dunia.
Ekspor capital di negara terjajah dan setengah-jajahan diarahkan pada pembangunan berbagai macam cabang industri yang melayani kepentingan negara-negara imperialis (industri ini utamanya adalah industri manufaktur, pengepakan ekspor bahan mentah dan pertanian, atau industri sekunder yang menyediakan barang konsumsi). Tumbuhnya industri ini yang melahirkan kelas baru yang maju secara ideologis di dalam masyarakat jajahan atau setengah jajahan yang masih berbasis sistem ekonomi lama, yaitu: feodalisme. Kelas baru tersebut adalah kelas proletar yang akan semakin berkembang dan mematangkan dirinya seperti comrade in arms-nya di negara-negara kapitalis industri melalui perjuangan kelas yang mereka lakukan bersama seluruh Rakyat
untuk menghancurkan musuh-musuh kelas mereka (borjuis besar komprador, tuan tanah feodal, dan kapitalis birokrat).
Dasar dari Gerakan Proletar di negari jajahan dan setengah jajahan adalah industri dengan teknologi terbelakang seperti yang ditransformasikan imperialisme tersebut. Karakter yang paling nyata industri tersebut adalah bukan industri dasar yang sanggup menmbangun industri-industri menengah dan kecil, kemudian mempunyai kepentingan ekonomi yang berorientasi pada ekspor bahan mentah, barang konsumsi manufaktur dengan teknologi rendah dan ekonomi impor yang bergantung pada penyediaan teknologi tinggi dan bahan jadi dari Negara imperialis. Dalam konsisi yang demikian kelas proletar harus membangun aliansi yang kokoh dengan kelas-kelas dan sektor-sektor tertindas lain di dalam masyarakat. Aliansi dasarnya adalah dengan kaum tani yang tertindas oleh sistem feodal dan setengah feodal lama. Namun dalam perjuangan revolusioner di negara tersebut kelas proletar tetap harus menjadi pimpinannya. Karena hanya kelas proletar yang mempunyai analisis yang lebih luas, program yang jelas untuk perubahan dan memiliki kepemimpinan yang kuat melalui partainya.
Kepemimpinan kelas proletar yang akan membawa jalannya revolusi di negeri jajahan dan setengah jajahan berkarakter revolusi demokratis borjuis tipe baru. Revolusi tersebut bersifat demokratis untuk menghancurkan basis sistem lama feodalisme yang telah berubah menjadi setengah feodalisme akibat dominasi imperialisme dan bersifat nasional karena akan menggerkan seluruh kelas dan kekuatan nasional anti-imperialisme di dalam negeri dengan aliansi dasar buruh dan tani di bawah pimpinan kelas proletar melalui partainya. Hari depan yang cerah menuju sosialisme telah menjadi jaminan bagi arah revolusi. Karena perspektif sosialisme di dalam revolusi demokrasi baru akan membawa seluruh kekuatan revolusioner di bawah pimpinan kelas proletar untuk melanjutkan tanpa jeda revolusi sosialis dan pembangunan sosialis setelah kemenangan total revolusi demokrasi baru. Dalam memimpin revolusi demokrasi baru, kelas proletar akan tampil dengan konsisten memimpin langsung perjuang revolusioner bersenjata kaum tani dalam revolusi agraria yang menjadi bagian terpokok dalam revolusi demokrasi baru untuk meruntuhkan basis kekuasaan ekonomi, politik, militer, dan budaya kaum borjuis besar komprador, tuan tanah feodal, kapitalis birokrat, dan imperialisme melalui negara bonekanya.
Demi terjaminnya kemenangan kelas proletar di seluruh dunia seperti yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat semenjak berdirinya Liga Komunis Internasional di tahun 1848. Maka kelas proletar di negara-negara kapitalis dan negara-negara jajahan dan setengah jajahan harus bersatu di bawah gerakan anti-imperialisme dunia dan membentuk
sebuah front persatuan anti-imperialisme di seluruh dunia. Sesuai dengan situasi sekarang di mana rantai terlemah dari imperialisme berada di negara-negara jajahan dan setengah jajahan, maka perjuangan revolusioner di negera-negara tersebut menjadi pusat gravitasi bagi gerakan anti-imperialisme se-dunia.
B.3 Apakah Revisionisme dan Oportunisme?Revisionisme adalah usaha-usaha yang secara sistematis dilakukan untuk merubah prinsip dasar Marxisme tentang perjuangan kelas dan revolusi dengan cara mengaburkan kontradiksi pokok dan antagonistik di suatu masyarakat yang harus diselesaikan oleh gerakan proletar, sehingga membingungkan strategi dan taktik gerakan proletar secara teoritis dan praktek. Aktivitas ini berada di dalam gerakan proletar itu sendiri.
Revisionisme klasik muncul pada Internasionale Kedua di tahun 1912 dengan bawah pimpinan utamanya Karl Kautsky dan Eduarde Bernstein. Mereka berada di dalam partai-partai sosial demokrat di negara-negara Eropa Barat yang mendukung rezim borjuis di negaranya untuk menaikkan anggaran militer dan memobilisasi seluruh rakyat (di mana mayoritas kelas proletar) untuk terlibat dalam Perang Dunia I. Mereka menyangkal hakekat revolusioner dari Marxisme dan pentingnya diktator proletariat untuk menjamin tercapainya sosialisme. Selain itu mereka juga mempropagandakan tentang reformisme borjuis dalam perjuangan melawan imperialisme yang pada hakekatnya menguntungkan politik kolonialisme dan neo-kolonialisme negara-negara imperialis. Dalam situasi gerakan proletar demikian ini, Kawan Lenin dengan tegas menentang teori dan praktek dari revisionisme yang berpura-pura sebagai marxis yang sejati. Melalui usaha yang brilian Kawan Lenin beserta kawan-kawan proletar revolusioner Rusia yang tergabung dalam Partai Bolshevik mempertahankan, memegang teguh, menjalankan dengan konsisten, dan mengembangkan Marxisme sebagai ideologi kelas proletar. Usaha ini dibuktikan dengan mendirikan negara sosialis pertama di dunia melalui kemenangan gemilang Revolusi Besar Sosialis Oktober 1917.
Revisionis modern terjadi di partai-partai komunis yang telah menang dan memimpin di Uni Soviet dan Eropa Timur. Mereka secara sistematis merevisi prinsip dasar Marxisme-Leninisme dengan cara menyangkal keberadaan kelas yang tertindas dan perjuangan kelas, dan karakter proletar revolusioner di dalam partai dan negara pada masyarakat sosialis. Mereka menghancurkan hasil karya massa rakyat dalam revolusi sosialis dan pembangunan sosialis dengan cara merestorasi kapitalisme di negara mereka. Dengan cara ini mereka menghancurkan partai kelas buruh dan negara yang dibangun dari darah dan keringat Rakyat dari dalam. Secara internasional, mereka seperti halnya para pendahulu mereka, kaum sosial-demokrat, di awal Abad XX, juga menyerukan untuk hidup berdampingan secara damai dengan imperialisme dan membuat ilusi bahwa sosialisme akan dapat dicapai melalui jalan legal-parlementer yang damai. Pernyataan ini mengingkari kenyataan tentang pertentangan kelas dan perjuangan kelas yang antagonistik di dalam masyarakat. Para tokoh utama revisionis modern adalah Joseph Bros Tito, Nikita Krushchov, dan yang mutakhir adalah Deng Xiaoping. Perdebatan antara Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet Kongres XX pada tahun 1956-1960-an dengan Kawan-kawan Proletar Revolusioner di dalam Partai Komunis Tiongkok di bawah pimpinan Kawan Mao Tsetung adalah puncak dari perselisihan paham yang berkembang menjadi kontradiksi yang antagonis. Kawan Mao tetap berpegang teguh pada prinsip dasar Marxisme-Leninisme tentang perjuang revolusioner melawan imperialisme. Di sini Marxisme-Leninisme mendapat sumbangan yang sangat berharga dari Pikiran-pikiranMao Tsetung untuk kemajuan gerkan proletar.
Basis dari revisionisme adalah pengaruh buruk ideologi borjuis kecil terhadap partai kelas proletar. Pengalaman menunjukkan bahwa revisionisme baik klasik maupun modern muncul dan berkembang ketika terjadi borjuasi terhadap partai dan gerakan kelas proletar. Borjuisasi terjadi karena mereka terjebak dalam serangan politik dan cultural kaum borjuis dalam praktek politik perjuangan kelas pada awal Abad XX. Sedangkan yang kedua terjadi karena tidak dipegang dengan teguhnya Marxisme-Leninisme sehingga partai komunis yang telah menang tidak dapat menjaga para kadernya yang hidup dalam standar borjuis karena memegang tampuk kekuasaan.
Revisionisme harus kita lawan untuk melakukan konsolidasi ideologi di dalam partai kelas proletar. Konsolidasi ideologi sangat diperlukan sebuah partai kelas proletar agar dapat meletakkan garis politik yang tepat bagi perjuangan revolusioner di negaranya. Garis politik ini yang akan mengklarifikasikan strategi dan taktik perjuangan revolusioner. Revisionisme membingungkan banyak kawan, sehingga gerakan menjadi inkonsisten dan terjadi demoralisasi kekuatan revolusioner. Revisonisme adalah penyimpangan di lapangan ideologi. Sedangkan dalam praktek di lapangan politiknya adalah oportunisme. Kita tidak dapat memisahkan perjuangan ideologi melawan revisionisme dan oportunisme dengan tugas sejarah kita melakukan perjuang revolusioner anti-imperialisme. Karena pada hakekatnya imperialisme tidak pernah berhenti menyerang gerakan proletar secara kultural (ideologis), dan bentuk nyata serangan mereka adalah membawa ide-ide borjuis masuk ke dalam gerakan proletar untuk melamahkannya seperti terjadi dalam pengalaman kita melawan revisionisme.
Untuk itu yang harus dilakukan gerakan proletar adalah berpegang teguh pada ideologi kelas proletar termaju dan tebukti mampu melawan revisionisme, oportunisme, dan liberalisme, yaitu Marxisme-Leninisme dan Pikiran-pikiran Mao Tsetung. Kemudian kita akan mempraktekkan teori tersebut sesuai dengan situasi kongkrit masyarkat kita, sehingga kita dapat memberikan kontribusi pengalaman yang berharga bagi gerakan proletar di seluruh dunia.
PENINDASAN FEODAL DAN SEMI-FEODAL TERHADAP PETANI DAN BURUH TANI1.1. Dasar Keberadaan Hubungan Produksi Penindasan Feodal1.1.1. Dasar Ekonomi Mencukupi Kebutuhan SendiriDalam sistem feodalisme, produksi dilakukan oleh kaum tani dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar sewa tanah terhadap tuan tanah yang menguasai tanah di mana dia bekerja. Kerja produksi yang dilakukan mempunyai nilai guna. Kelebihan dari hasil produksi yang telah dikonsumsi oleh keluarga atau untuk
membayar sewa tanah, baru dijual ke pasar. Para tuan tanah akan mendapatkan bagian yang besar dari pembayaran sewa tanah hasil produk lebih (surplus product) yang dibayarkan oleh kaum tani. Para perajin memproduksi barang konsumsi untuk dijual ke pasar, namun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia juga berproduksi di tanah. Dan bagi kaum perajin yang tinggal di kota atau pusat perputaran barang produksi masih menggantungkan kebutuhan hidupnya terutama bahan pangan dari pedesaan. Komunitas masyarakat dalam sistem ini bersifat mandiri secara relatif. Karena sebagian besar masyarakat berproduksi secara independen dengan teknologi produksi yang terbelakang dan dihisap oleh segilintir elemen dalam masyarakat yaitu kelas tuan tanah.
1.1.2. Monopoli penguasaan Tanah
Dalam sistem feodalisme, alat produksi utama yang menentukan masyarakat adalah tanah. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Sebagian petani menguasai tanah yang kecil-kecil untuk dikerjakan oleh tenaganya sendiri. Sebagaian besar petani selain menggarap lahannya sendiri yang kecil dan terbatas (bahkan banyak di
antara mereka yang sama sekali tidak menguasai atau memiliki tanah untuk dikerjakan) harus menggarap lahan tuan tanah yang jauh lebih luas untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Karena itu para petani harus membayar sewa tanah kepada tuan tanah.
1.1.3. Produksi dalam Skala Kecil dan Mandiri
Petani bergantung pada alat kerja yang sederhana yang dikembangkan untuk berproduksi secara sendiri-sendiri, karena mereka berproduksi terpisah satu sama lain dalam petak-petak tanah. Maka produksinya kecil dan terbatas. Perkembangan teknologi alat kerja tidak bisa berkembang pesat, sehingga sangat terbelakang.
1.2. Setengah FeodalHubungan kapitalistis yang muncul di dalam sistem feodalisme, akan tetapi hubungan produksi feodal masih bersisa secara meluas di pedesaan. Sistem feodalisme telah didisintegrasikan namun sistem kapitalisme tidak dapat mendominasi secara komplet. Maksud dari hubungan produksi kapitalis adalah bagaimana kapital berefek pada hubungan produksi, tetapi tetap ada hubungan penindasan antara tuan tanah dengan petani. Dalam setengah feodal, ekonomi mencukupi kebutuhan sendiri (nilai guna) tidak terlalu mendominasi atau bahkan telah dihapuskan. Produk pertanian dari petani diperjualbelikan di pasar. Pengembangan kapitalis tidak bisa secara utuh, karena sisa-sisa feodalisme yang terbelakang masih mencengkeram dengan kuat terutama di pedesaan. Dalam sistem ini buruh tani perkebunan/maritim (proletariat desa) dan semi-proletariat juga muncul untuk “menjual tenaganya sebagai kerja produksi yang sekunder”.
Sistem setengah feodal muncul akibat dominasi dari imperialisme dalam masyarakat feodal lama. Imperialisme tidak menghancurkan masyarakat feodal lama menjadi sistem kapitalisme. Karena imperialisme hanya membutuhkan bahan mentah yang melimpah, tenaga produksi yang murah dan luasnya pasar bagi produk mereka. Ekonomi mencukupi kebutuhan sendiri diganti dengan ekonomi yang berbasis pada uang. Efeknya produk kerajinan lokal tidak bisa berkembang dan hancur karena harus bersaing dengan produk imperialis yang berteknologi tinggi, mudah dan murah yang diimpor dengan ekonomi berbasis uang untuk ditukar dengan produksi bahan mentah dan produk pertanian.
Di pedesaan kapital berwujud sebagai riba dan perdagangan produk pertanian atau bahan mentah. Di dalam setengah feodal tidak terdapat industri dasar (basic industry). Industri yang ada adalah manufaktur, perakitan, pengepakan yang berorientasi ekspor. Secara nasional industri sangat bergantung pada impor akan tekonologi dan mesin produksi yang maju. Perdagangan didominasi oleh para borjuis besar komprador, dengan konsentrasi pada ekspor produk pertanian, bahan mentah, dan produk hasil manufaktur. Persoalan tanah (secara umum agraria) adalah masalah utama masyarakat sistem ini. Elemen kelas penguasa setengah feodal, yaitu tuan tanah dan sebagian tani kaya masih menggunakan cara berpikir feodal dalam mengakumulasi kekayaan. Kalau mereka mempunyai pendapatan yang berlebih digunakan untuk memiliki atau menguasai tanah yang lebih luas, karena kemampuan mereka berusaha di luar pertanian sangat kecil. Walaupun sebagian ada yang menanamkan saham pada sektor perdagangan untuk menjadi borjuasi besar komprador.
1.3. Sewa Tanah dan Berbagai Bentuk Penindasan FeodalImperialisme di Indonesia pernah melakukan liberalisasi tanah di tahun 1870 yang mengatur tentang kepemilikan partikelir. Namun hal tersebut tetap tidak merubah struktur sistem feodalisme di Indonesia karena tetap saja ada monopoli penguasaan dan pemilikan tanah yang mempertahankan masyarakat feodal lama dan hubungan penindasannya. Sewa tanah adalah bentuk dasar hubungan penindasan feodal. Apakah sewa tanah?
Sewa tanah adalah beban yang harus dibayar oleh petani penggarap atau buruh tani kepada tuan tanah feodal yang menguasai tanah tersebut, karena para petani mendapat “izin” untuk menggarapnya. Bentuk pembayaran beban tersebut bisa berwujud uang atau barang. Tuan tanah feodal yang menentukan bentuk pembayarannya. Misalnya
berwujud bagi hasil panen pertanian (di Jawa dikenal dengan sistem maro atau bagi paruh, mrapat atau 25:75, 25% bagian untuk petani dan 75% bagian untuk tuan tanah feodal), membayar pajak atas “hak” menggarapnya, membeli tahunan atas sebidang tanah (sebagai ungkapan penghalusan untuk persewaan tanah), dan lain-lain.
Untuk menaikkan sewa tanah, tuan tanah feodal memaksa petani untuk memikul biaya produksi pengolahan tanah (bibit, pupuk, pestisida, alat kerja pertanian). Di beberapa tempat karena mengakarnya sistem feodal lama, bahkan petani juga dibebani untuk memberikan pengabdian secara cuma-cuma kepada tuan tanah.
Sewa tanah bukan merupakan profit atau laba yang didapat tuan tanah dari produksi pertanian. Karena di dalam produksi pertanian sistem feodalisme tanah bukan merupakan kapital, dan tuan tanah memperoleh sewa tanah dari produk lebih (surplus product) pertanian yang dikerjakan oleh petani secara cuma-cuma dan tanpa bekerja (petani yang bekerja mendapat hasil produksi, namun sebagian besar hasil panennya untuk tuan tanah feodal). Tuan tanah tidak perlu menanam modal dan berpartisipasi langsung dalam produksi namun akan mendapat bagian yang besar dalam produksi pertanian. Sewa tanah adalah pajak yang secara paksa ditetapkan oleh tuan tanah feodal karena monopoli penguasaan tanah tanpa kapital. Tanah berbeda dengan mesin produksi dalam sistem kapitalisme, karena mesin ketika dioperasikan oleh kelas proletar sanggup memproduksi barang yang menambah nilai baru dari kapital tersebut dan dan berkembang maju. Sedangkan tanah adalah sasaran kerja yang statis perkembangannya dan tidak akan bernilai baru walaupun telah dikerjakan oleh petani.
Perkembangan alat produksi dapat menambah keuntungan tanpa harus menurunkan upah buruh. Tapi dalam sewa tanah hanya dapat ditingkatkan melalui menurunkan produk yang dibutuhkan oleh petani atau menurunkan upah buruh tani. Misalnya: Hasil panen adalah 1000 kg beras, dengan bagi hasil 70:30. Akan tetapi tuan tanah membutuhkan 400 kg lagi untuk hasil panen selanjutnya. Maka dia akan potong jatah petani untuk panen sekarang dan panen yang akan datang. Sehingga sekali lagi sewa tanah bukan merupakan nilai produksi tanah. Tanah akan memiliki nilai bila memobilisasi tenaga produksi dalam pengembangannya (memaksa petani berkerja di sana). Atau dengan kata lain tanah akan bernilai bila ada kapital (dalam alat kerja) dan kerja yang dilakukan oleh petani dan buruh tani.
Tuan tanah feodal memperluas penguasaan tanahnya melalui perampasan tanah (land grabbing) yang sebagian besar metodenya adalah kekerasan dan pemaksaan oleh alat kelasnya, yaitu mesin-mesin negara reaksioner. Karena adanya monopoli tanah, maka tanah menjadi terbatas dan menjadi komoditi di pasar. Monopoli tanah, sewa tanah, dan harga tanah menghambat produksi walaupun dalam masyarakat kapitalis.
Di dalam sistem setengah feodal terdapat pertanian atau perkebunan yang dikelola secara hubungan produksi feodal dan ada pula yang secara hubungan produksi kapitalis. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan tipe sewa tanah. Perbedaannya adalah bila sewa tanah feodal berbasis pada hubungan poduksi feodal, bentuk utamanya adalah produk lebih dalam sistem feodalisme, dan diproduksi tanpa investasi. Sedangkan dalam sewa tanah kapitalis adalah berbasis hubungan produksi kapitalis, hanya sebagian dari nilai lebih dan kuantitasnya ditentukan oleh laba, dapat diekstraksi (diperoleh secara berlebihan melalui penghisapan) dari penggunaan kapital dalam produksi. Maka dalam sewa tanah kapitalis, produksi selalu dipaksa untuk ditingkatkan agar mereka dapat mengutip pajak yang tinggi dari pertani atau buruh tani yang bekerja.
Bentuk lain penghisapan feodalisme adalah peribaan. Peribaan marak terjadi karena petani miskin, buruh tani dan golongan lain di pedesaan dipaksa untuk meminjam uang pada lintah darat untuk mencukupi biaya produksi pengolahan pertanian (beli pupuk, bibit, dan lain-lain) atau untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena dia tidak dapat memperoleh bagian hasil panen yang cukup. Di pedesaan sangat wajar bila seorang tuan tanah juga merupakan seorang lintah darat, karena dia adalah salah satu pihak yang memiliki kelebihan penghasilan dari produk lebih yang didapatnya melalui sewa tanah. Program perkreditan untuk biaya produksi pengolahan pertanian dari pemerintah reaksioner secara hakekat juga merupakan peribaan, karena negara ini menjadi alat dari kelas taun tanah dan borjuis besar komprador.
Jaminan dari peminjam dalam peribaan dapat wujudnya bermacam-macam. Bagi tuan tanah yang juga seorang lintah darat ini digunakan sebagai cara untuk memperluas penguasaan tanah dan menancapkan kendali secara kuat terhadap petani. Apabila petani tidak sanggup membayar bunga pinjamannya dan pinjaman pokoknya, maka sepetak tanah sebagai jaminannya akan disita oleh tuan tanah. Atau bila si peminjam adalah buruh tani akan bekerja tanpa bayar atau dipotong bagian bagi hasilnya. Sehingga tuan tanah tidak hanya mendapat produk lebih saja, namun akan juga mendapat bagian dari peribaan yang dilakukannya. Petani yang terjerat hutang akan kesulitan mengembangkan produksi pertanian. Dan secara politik mereka berada di bawah kekuasaan tuan tanah feodal.
1.4. Bentuk-bentuk Lain Penghisapan Semi-Feodal di Pedesaan1.4.1. Sistem Pengupahan ala Budak Bagi Buruh TaniSemenjak mayoritas populasi di desa mencari kerja karena tersingkir dalam berpartisipasi produksi di pertanian karena monopoli penguasaan tanah oleh kelas tuan tanah feodal, maka terjadi tenaga kerja lebih (surplus labour) dan jumlah petani yang menjual tenaganya semakin meningkat. Hanya sedikit dari mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, selebihnya adalah musiman. Ini merajalela di daerah dahulunya lahan pertanian biasa yang dirubah menjadi perkebunan besar, pabrik, pemukiman atau daerah non-sektor pertanian lainnya.
Dari situasi tenaga kerja lebih ini posisi tawar petani menjadi sangat rendah. Pendidikan yang sangat mahal dan sama sekali tidak mengarahkan pada pembebasan petani dari keterbelakangan teknologi pertanian, penyediaan sarana pelayanan masyarakat yang sangat parah (terutama tentang kesehatan, rekreasi umum, transportasi, dan lainlain), semakin membuat kondisi pedesaan menjadi daerah terbelakang yang terus dihisap dan ditindas untuk kepentingan imperialisme dan kelas-kelas reaksioner dalam negeri.
Kondisi buruh tani (termasuk di dalamnya buruh perkebunan, peternakan besar, nelayan) sangat buruk. Upah yang mereka dapatkan jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya, jam kerja yang tidak hanya menuruti kemauan tuan tanah feodal dan pemilik perkebunan besar, serta lingkungan kerja yang sangat buruk tanpa jaminan keselamatan kerja bagi mereka. Kebebasan berorganisasi pun sangat dibatasi, apalagi di Indonesia setiap gerakan yang mereka buat selalu disangkutkan oleh birokrat kepala batu desa (militer dan aparat sipil negara reaksioner) maupun tuan tanah dengan sepak terjang Barisan Tani Indonesia (organisasi massa tani militan, patriotik yang menjadi onderbouw Partai Komunis Indonesia saat mengalami masa kesalahan oportunisme “kiri” dan kanan di tahun 1960’an). Secara umum buruh tani masuk ke dalam kaum tani, karena mereka merupakan bagian kekuatan produksi yang masuk dalam hubungan produksi penindasan
feodalisme.
Adapun kelas tuan tanah di dalam sistem setengah feodal mengalami perubahan, karena adanya hubungan kapitalistik di dalam hubungan produksi feodal. Di sistem ini terdapat tuan tanah feodal tipe lama, yaitu tuan tanah feodal yang mendapatkan sewa tanah feodal dari kaum tani dan buruh tani. Dan tuan tanah feodal tipe baru, yaitu tuan tanah feodal yang telah memiliki kapital dalam jumlah yang terbatas (dapat pula yang telah menjadi borjuis besar komprador) dan juga mendapat laba di samping sewa tanah hasil produk lebih pertanian dari petani dan buruh tani. Tuan tanah feodal tipe baru juga bergantung dari monopoli tanah untuk tambahan pendapatannya. Di samping itu adapula para mandor yang membantu tuan tanah untuk menghisap petani atau tenaga administratif perkebunan besar lain yang memainkan peran represif dalam menjalankan hubungan produksi penindasan feodal.
Di dalam perkebunan besar atau pertanian kapitalis muncul para makelar tenaga kerja yang mencarikan buruh tani bagi tuan tanah atau kapitalis pertanian (sebagian besar adalah borjuis besar komprador). Mereka ini yang langsung berhubungan dengan petani dan mengeruk keuntungan lebih dari tuan tanah dan kapitalis pertanian, sekaligus dari petani sebagai jasa mereka “mencarikan pekerjaan” dari upah atau kutipan lainnya. Sikap kita adalah menetralisasikan mereka. Golongan yang lain adalah tani kaya, yaitu mereka yang mempunyai tanah luas, namun berpartisipasi aktif dalam berproduksi di tanah tersebut. Walaupun begitu dia juga menindas petani dan buruh tani melalui sewa tanah dan upah buruh a la perbudakan. Sikap kita adalah menetralisasikan mereka.
Selanjutnya adalah golongan petani menengah dan miskin, mereka ditolong oleh buruh tani, mereka tidak mengambil produk lebih (bahkan mereka harus membayar sewa tanah bila menjadi petani penyakap). Sepertihalnya buruh tani mereka tertindas. Dan bersamasama buruh tani harus bangkit, bergerak, berorganisasi dan melawan kekuasaan tuan tanah feodal secara politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer.
1.4.2. Penindasan TengkulakProduk pertanian yang ada di pedesaan dibeli oleh para tengkulak untuk dipasarkan ke kota. Mereka membeli dengan harga yang mereka tentukan sendiri (dengan berbagai alasan, biaya transportasi, harga pasaran, dan lain-lain). Para petani terpaksa harus menjual produknya kepada mereka, karena akses yang rendah ke kota. Tengkulakisme merajalela pada pertanian kecil dan terpisah-pisah. Di samping itu para tengkulak juga meminjamkan benih, pupuk, pestisida atau alat kerja pertanian pada petani dengan bunga yang tinggi seperti sistem peribaan. Pada saat revolusi hijau dicanangkan merek adalah mitra dari pemerintahan reaksioner dan komprador kepentingan imperialisme di pedesaan. Mereka adalah mata rantai yang penting bagi tuan tanah, borjuis besar komprador, dan imperialisme, karena mereka jual alat produksi pengolahan pertanian dari imperialis dan juga membeli bahan mentah pertanian dari petani untuk menyediakan kebutuhan imperialis dan borjuis besar komprador. Sikap kita adalah menetralisasikan mereka.
2. REVOLUSI AGRARIA DAN PEMBANGUNAN SOSIALISME DI PEDESAAN2.1. Revolusi AgrariaRevolusi agraria adalah perjuangan revolusioner yang dilakukan oleh petani dan buruh tani untuk menghancurkan kekuasaan tuan tanah feodal di pedesaan dan menghancurkan hubungan produksi penindasan feodalisme dan setengah feodal. Dengan menghancurkan kekuasaan politik tuan tanah di pedesaan, revolusi agraria juga menghancurkan monopoli penguasaan tanah yang menjadi inti hubungan produksi feodal
dan setengah feodal. Ini adalah satu-satunya jalan revolusioner yang ditempuh untuk memecahkan persoalan agraria di masyarakat. Tujuan utamanya adalah menyita tanah dari kekuasaan tuan tanah dan imperialis dan membagikan kepada petani dan buruh tani untuk digarap dan secara bertahap akan ditingkatkan menjadi produksi pertanian kolektif dengan semangat pembangunan sosialisme. Prinsipnya adalah kepemilikan setara dari negara Republik Demokrasi Rakyat Indonesia. Pemerintahan Republik Demokrasi Rakyat Indonesia yang akan mengatur hak yang merdeka bagi seluruh rakyat untuk menggarap dan memanfaatkannya.
Karena menghancurkan fondasi sistem feodalisme dan setengah feodalisme, maka revolusi agraria menjadi bagian integral yang sangat penting bagi Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia. Sebagai bentuk perjuangan pokok, revolusi agraria tidak dapat dimenangkan dengan jalan legal. Akan tetapi harus dilakukakan melalui perjuangan bersenjata dan pembangunan organ kekuasaan politik. Karena ketiganya (perjuangan bersenjata, pembangunan organ kekuasaan politik, dan revolusi agraria) merupakan komponen Perang rakyat Jangka Panjang yang menjadi strategi umum Revolusi Demokrasi Rakyat di negeri setengah feodal dan setengah jajahan.
Dengan tujuan yang sedemikian hebat revolusi agaria tidak dapat dilakukan dalam sekali waktu, namun harus bertahap sesuai dengan perkembangan kemajuan kekuatan revolusioner rakyat. Untuk itu revolusi agraria memiliki program minimum dan program maksimum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan kemajuan Revolusi Demokrasi Rakyat melalui Perang Rakyat Jangka Panjang. Program minimumnya adalah menurunkan sewa tanah, menghapuskan peribaan, menaikkan upah buruh tani, melawan kecurangan tengkulak. Dengan jalan membangun koperasi sederhana dan kolektif produksi melalui organisasi tani, dan membentuk serikat buruh pada pertanian kapitalis. Sedangkan program maksimum adalah menyita tanah yang dilanjutkan dengan pembagian hak menggarap merdeka dan bila sudah siap membangun kolektif produksi pertanian. Dalam perjuangan revolusi agraria, pengembangan dan pembangunan kekuatan produksi adalah tujuan yang utama.
2.2. Kebutuhan untuk Melakukan Pembangunan Sosialisme di Pertanian
Transformasi sosialis adalah kunci sebelum melakukan pembangunan sosialisme di pedesaan dan sektor pertanian. Transformasi sosialis akan memberikan petani dan buruh tani pembebasan sepenuhnya dari kemiskinan dan kondisi terbelakang yang diciptakan oleh foedalisme/setengah feodalisme. Wujud nyata dari transformasi sosialis adalah kampanye kolektifikasi produksi, walaupun Revolusi Demokrasi Rakyat masih berlangsung. Karena selama masih terdapat penggarapan tanah yang individual, maka masih ada produksi pertanian yang terbelakang, sehingga mesin dan teknologi produksi yang maju dan modern tidak dapat digunakan secara meluas untuk memajukan sektor produksi pertanian dalam masyarakat.
Setelah kemenangan Revolusi Demokrasi Rakyat, akan dilanjutkan dengan Revolusi Sosialis/Pembangunan Sosialisme. Di babak ini transformasi sosialis yang telah ditanamkan sejak masa sebelumnya menjadi tombak keberhasilannya. Karena kolektifikasi kepemilikan tanah dan alat kerja pertanian akan dilaksanakan, kolektikasi prouksi dan pembangunan produksi adalah tugas dari transformasi sosialis. Ini adalah awal dari pembangunan pedesaan sebagai benteng sosialisme dan peningkatan kondisi kehidupan petani. Pembangunan pertanian yang cepat akan mempengaruhi percepatan pembangunan dari seluruh masyarakat. Untuk menjaga proses ini, ideologisasi terhadap massa di pedesaan harus dilakukan melalui pendidikan dan praktek kolektifikasi produksi semenjak masa Revolusi Demokrasi Rakyat.
“Kaum Buruh Seluruh Dunia, Bersatulah!!!”